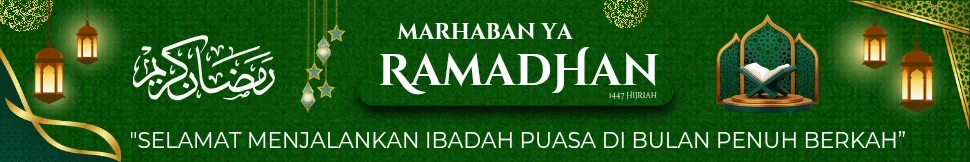OPINI—Penonaktifan sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) bukan sekadar persoalan administratif. Kebijakan ini mencerminkan kegagalan sistem kapitalisme dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat, khususnya layanan kesehatan.
Ketika jutaan warga miskin tiba-tiba kehilangan akses pelayanan, termasuk pasien cuci darah yang bergantung pada terapi rutin untuk bertahan hidup, yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar data, melainkan nyawa. Ironisnya, banyak pasien tidak menerima pemberitahuan sebelumnya.
Sebagaimana dilansir Kompas.id pada 7 Februari 2026, Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), Tony Richard Samosir, menyatakan sebagian besar pasien cuci darah yang kepesertaannya dinonaktifkan tidak memperoleh pemberitahuan. Pemutusan mendadak tersebut dinilai tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia.
Di balik kebijakan ini, pemerintah berdalih penonaktifan dilakukan untuk verifikasi dan pemutakhiran data. Secara teknis, pembaruan data memang diperlukan. Namun, dalam praktiknya, kebijakan tersebut menunjukkan watak sistem yang menempatkan administrasi di atas kemanusiaan.
Reaktivasi kepesertaan mengharuskan pasien mengurus berbagai dokumen ke Dinas Sosial, termasuk surat keterangan tidak mampu dari RT, RW, hingga kelurahan. Bagi rakyat miskin yang tengah berjuang melawan penyakit kronis, prosedur ini menjadi beban tambahan yang melelahkan dan tidak manusiawi.
Rumah sakit pun berada dalam posisi sulit. Mereka diminta tetap melayani pasien yang dinonaktifkan, tetapi tanpa jaminan pembiayaan. Dalam skema asuransi sosial seperti BPJS Kesehatan, pelayanan sangat bergantung pada kepastian klaim.
Ketika status kepesertaan nonaktif, tidak ada pihak yang menanggung biaya. Akibatnya, pasien terombang-ambing di antara kebijakan negara dan realitas pembiayaan layanan medis.
Situasi ini memperlihatkan karakter sistem kapitalisme dalam sektor kesehatan, yakni menjadikan layanan kesehatan sebagai komoditas. Akses terhadap layanan ditentukan oleh kemampuan membayar atau status administratif yang menjamin pembayaran.
Negara tidak hadir sebagai penanggung jawab langsung, melainkan sebagai regulator yang mengelola mekanisme pembiayaan. Ketika terjadi pemutakhiran atau “pembersihan data”, rakyat miskin menjadi kelompok paling rentan terdampak.
Dalam sistem kapitalisme, kesehatan dipandang sebagai sektor biaya yang harus dikelola secara efisien. Anggaran dibatasi, subsidi diseleksi, dan penerima bantuan terus diverifikasi dengan kriteria ketat.
Akibatnya, hak hidup rakyat rentan tereduksi menjadi variabel fiskal. Penonaktifan jutaan peserta PBI menunjukkan bahwa keselamatan jiwa dapat tertunda oleh persoalan administratif.
Islam memandang persoalan kesehatan secara mendasar dan berbeda. Dalam Islam, negara berperan sebagai raa‘in (pengurus) yang bertanggung jawab langsung atas rakyatnya. Rasulullah Saw. bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan kesehatan bukan sekadar kebijakan pilihan, melainkan kewajiban syar‘i. Negara tidak dibenarkan menyerahkan urusan vital ini kepada mekanisme pasar atau logika untung-rugi.
Al-Qur’an juga menempatkan perlindungan jiwa (hifzh an-nafs) sebagai tujuan utama syariat. Allah Swt. berfirman:
“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar.” (QS. al-An‘am: 151)
Ayat ini menegaskan prinsip perlindungan jiwa secara menyeluruh. Kebijakan yang berpotensi membahayakan keselamatan manusia akibat kelalaian atau pembiaran bertentangan dengan prinsip tersebut.
Dalam paradigma Islam, kesehatan merupakan kebutuhan pokok yang wajib dijamin negara bagi setiap individu, tanpa membedakan kaya atau miskin.
Negara mengelola layanan kesehatan secara langsung dan membiayainya melalui baitulmal, yang bersumber dari fai, kharaj, serta pengelolaan kepemilikan umum seperti sumber daya alam. Dengan mekanisme ini, akses layanan kesehatan tidak bergantung pada status administratif yang sewaktu-waktu dapat dinonaktifkan.
Jika dana baitulmal tidak mencukupi, negara diperbolehkan memungut pajak temporer dari kaum muslimin yang mampu untuk memenuhi kebutuhan darurat. Dengan demikian, keselamatan jiwa ditempatkan sebagai prioritas utama, bukan sekadar variabel administratif atau fiskal.
Penonaktifan PBI, karena itu, bukan hanya kesalahan teknis, melainkan cermin kegagalan sistem kapitalisme dalam memandang kesehatan sebagai hak dasar. Selama layanan kesehatan ditempatkan dalam kerangka pembiayaan dan logika pasar, kebijakan akan terus berpotensi merugikan kelompok paling lemah.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut pembaruan data atau perbaikan administrasi, tetapi juga menyentuh cara pandang mendasar terhadap kesehatan. Selama kesehatan diperlakukan sebagai komoditas, ia akan tunduk pada logika untung-rugi dan daya beli, bukan pada kebutuhan kemanusiaan.
Yang dibutuhkan bukan sekadar pembenahan teknis, melainkan perubahan paradigma. Kesehatan harus dikembalikan sebagai hak rakyat yang wajib dijamin negara. Negara tidak cukup hadir sebagai pengelola administrasi, tetapi harus berperan sebagai penjaga keselamatan jiwa, memastikan setiap warga memperoleh layanan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi.
Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa rumah sakit dibangun dan dikelola negara serta terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa pungutan biaya. Pelayanan medis, obat-obatan, hingga perawatan lanjutan diberikan sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Model ini menegaskan bahwa ketika paradigma bergeser dari komersialisasi menuju tanggung jawab negara, kesehatan benar-benar menjadi prioritas.
Dengan demikian, perubahan mendasar hanya dapat terwujud jika sistem yang mendasarinya turut berubah. Selama kesehatan tunduk pada logika pasar, rakyat akan terus dibayangi ketidakpastian akses layanan.
Sebaliknya, ketika negara menjalankan tanggung jawabnya secara penuh, kesehatan menjadi bagian dari amanah kepemimpinan, dan rakyat tidak lagi dipaksa memikirkan biaya untuk mempertahankan hidupnya. Wallahu a’lam. (*)
Penulis:
Hamsina Halik
(Pemerhati Sosial)
Disclaimer:
Setiap opini, artikel, informasi, maupun berupa teks, gambar, suara, video, dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab masing-masing individu, dan bukan tanggung jawab Mediasulsel.com.